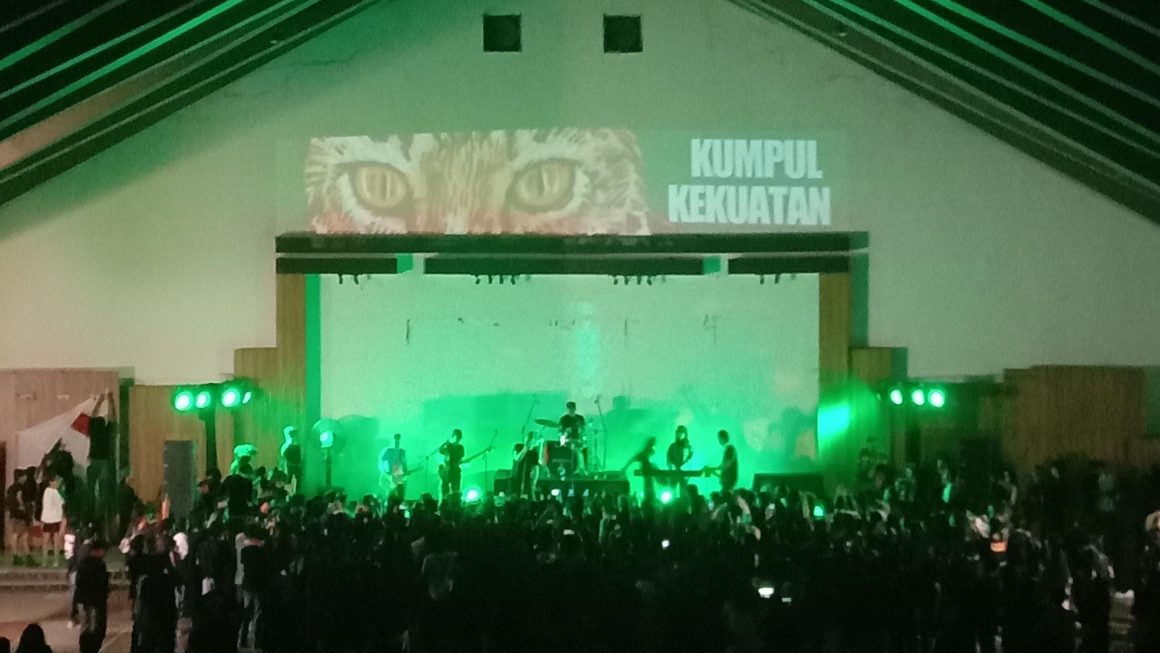Kamis (22/9/22), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (BEM FIB Undip) menggelar diskusi di Crop Circle FIB Undip bertema “Musik sebagai Media Perlawanan terhadap Ketidakadilan” dengan pemantik Gregorius Tri Hendrawan Manurung, mahasiswa Sastra Indonesia 2018 sekaligus Redaktur Highvolta Media.
Sebagai pembuka, Gregorius menyampaikan pandangannya mengenai irisan-irisan musik dengan politik. Menurutnya, politik tidak sebatas hal negara, struktur pemerintahan, atau perebutan kekuasaan dalam bentuk yang kaku. Tetapi juga tentang pengambilan sebuah keputusan yang di dalamnya terdapat dimensi secara personal mengenai kekuasaan atas diri sendiri.
“Karena bagiku politik adalah sikap yang sangat personal. Sehingga ketika politik hanya dekat dengan hal-hal yang besar saja, maka definisi politik itu belum beres,” ujarnya.
Sementara itu, musik sebagai medium untuk melawan ketidakadilan pun menurutnya tak terlepas dari kepercayaan politik sang kreator/musisi yang kemudian dituang dalam sebuah lagu.
Menelisik jauh ke belakang, Gregorius memaparkan sejarah adanya musik hip-hop yang pada zamannya menjadi media orang kulit hitam di Amerika Serikat yang terdiskriminasi untuk menyatakan sikap politiknya.
“Pada 1977 di New York ada pemadaman listrik besar-besaran, disebut New York Blackout of 1977, terus orang-orang kulit hitam di Bronx menjarah toko-toko yang ada di sana. Ketika orang-orang tua mengambil kulkas, kipas angin, misalnya, anak-anak mudanya mengambil piringan hitam (vinyl) dan turntable atau alat pemutar piringan hitam itu. Para pemuda ini bikin party di pinggir jalan dan memproduksi [musik] di apartemen-apartemen mereka dengan hasil jarahan tersebut. Ada satu DJ, disebut DJ Kool Herc yang mulai membentuk musik hip-hop. Ketika mereka mendapat gaya musik yang mereka inginkan, di situ mereka menyuarakan lagi kepercayaan politik mereka soal brutalitas kepolisian Amerika,” jelas Gregorius.
Beralih ke Indonesia, menurut Gregorius secara historis musik sebagai perlawanan terbagi dalam dua hal, “kecelakaan” dan “sengaja”. Musik yang “kecelakaan” dibuat oleh kreator yang hanya ingin membuat musik tanpa tendensi apapun, namun ternyata ada irisan politik yang terjadi di satu masa dan tempat yang sama.
“Salah satunya adalah Koes Plus yang pernah dipenjara Soekarno karena nyanyi lagu ngak ngik ngok: itu istilah untuk musik yang banyak mengambil unsur Barat. Koes Plus suka The Beatles. Pada albumnya Kelelawar, unsur The Beatles sangat terasa. Lalu akhirnya dia dipenjara,” lanjutnya.
Di sisi lain, ada musik yang memang bertendensi kritik. Ia menyebutkan misalnya lagu-lagu dari The Gang of Harry Roesli. “Pada tahun 1970-an dia bikin album Philosophy Gang, ada lagu instrumental sembilan menit judulnya Don’t Talk About Freedom. Dia mencoba menggambarkan kondisi saat itu di mana Soeharto seperti menyelamatkan Indonesia pada 1966, dan dia membuka banyak keran produk kultural dari Barat, investasi asing, dan lain sebagainya,” terangnya.
“Saat itu juga ada bom kelas menengah karena harga minyak dunia naik dan cadangan minyak Indonesia lagi tinggi, jadi perekonomian Indonesia pun naik. Jadi, kan, terlihat ‘Wah, lagi masa bebas-bebasnya, nih, mau lakuin apa aja.’ Tapi banyak hal juga yang tidak diketahui atau dibicarakan. Makanya jadi Don’t Talk about Freedom,” lanjutnya.
Setiap gerakan sosial memiliki lagu tersendiri, karena musik sebagai bagian dari seni memiliki daya magis yang mampu membuat manusia merenung kembali, katanya. “[Gerakan sosial] kalau lokal itu banyak, misalnya Festival Kampung Kota di Bandung tahun 2017 dan 2019. Di mana beberapa band dari Bandung dan luar kota membuat festival sebulan penuh di titik-titik penggusuran. Tahun 2017 di Dago Elos dan 2019 di Tamansari,” ujarnya.
Alih-alih hanya bermain musik selama satu bulan di titik penggusuran, selain diskusi dan workshop, ada juga poin penting yang didapat oleh para pemain band-band tersebut, yaitu pengalaman. “Dengan membawa para musisi ke titik penggusuran, mereka dapat merasakan perasaan orang-orang yang digusur, apa saja yang hilang, seperti relasi sosial yang sudah terbangun antar warga dan juga mata pencaharian,” katanya.
“Kupikir musik punya kekuatan di ranah itu, ketika dia bisa secara langsung hidup di titik-titik krisis yang ada. Apa yang ditawarkan oleh karya seni adalah pengalaman. Pengalaman riil yang kita dapatkan ketika kita benar-benar menjadi orang asing yang tidak tahu apa-apa dan mengalami satu peristiwa secara utuh,” lanjutnya.
Musik pun menurutnya mampu masuk ke ruang-ruang personal manusia, seperti pengalaman ketertindasan. “Misalnya salah satu lagu dari musisi Semarang, namanya Kanina. Judulnya And I’m Not Sorry, itu menggambarkan pelecehan seksual, tetapi pada saat yang sama dia seperti berdialog dengan penyintas. Karena biasanya masih banyak anggapan bahwa kesalahan itu milik korban. Tapi dengan cerdas, Kanina menaruh kata-kata “I’m not sorry” di reff dan judulnya yang menyatakan bahwa, ‘Nggak, kok, gue nggak salah, lo yang salah. Gue berpakaian gini karena ingin, bukan buat narik sorotan mata lo. Dan itu bukan hal yang salah,’” ungkap Gregorius.
Ketika musik berhasil mencapai ranah personal, ia melanjutkan, dapat dikatakan bahwa musik memang berdialog dengan individu itu sendiri. Musik menjadi hasil pengalaman dari seorang kreator. Jika dilihat lebih jauh, musik adalah produk kultural yang tidak datang secara tiba-tiba tanpa ada proses yang melatarbelakangi itu. “Musik sebagai respons zaman atau dokumentasi zaman,” kata Gregorius.
Ia juga menambahkan bahwa, “Kalau sebagai penanda perubahan itu masih terburu-buru, kita nggak tahu. Dia (musik) bisa jadi penanda zaman, tapi apakah dia penanda perubahan? Itu harus dikaji lebih jauh lagi. Perubahan, kan, bisa jadi 500 tahun, misal. Apakah selama 500 tahun itu nggak ada musik yang diciptakan? Pasti ada, dong. Apakah ada perubahan selama 500 tahun itu? Ya, nggak tahu juga. Dokumentasi sosial, mungkin iya. Penanda perubahan, entar dulu,” pungkasnya.
Reporter: Juno
Penulis: Suci
Editor: Rilanda