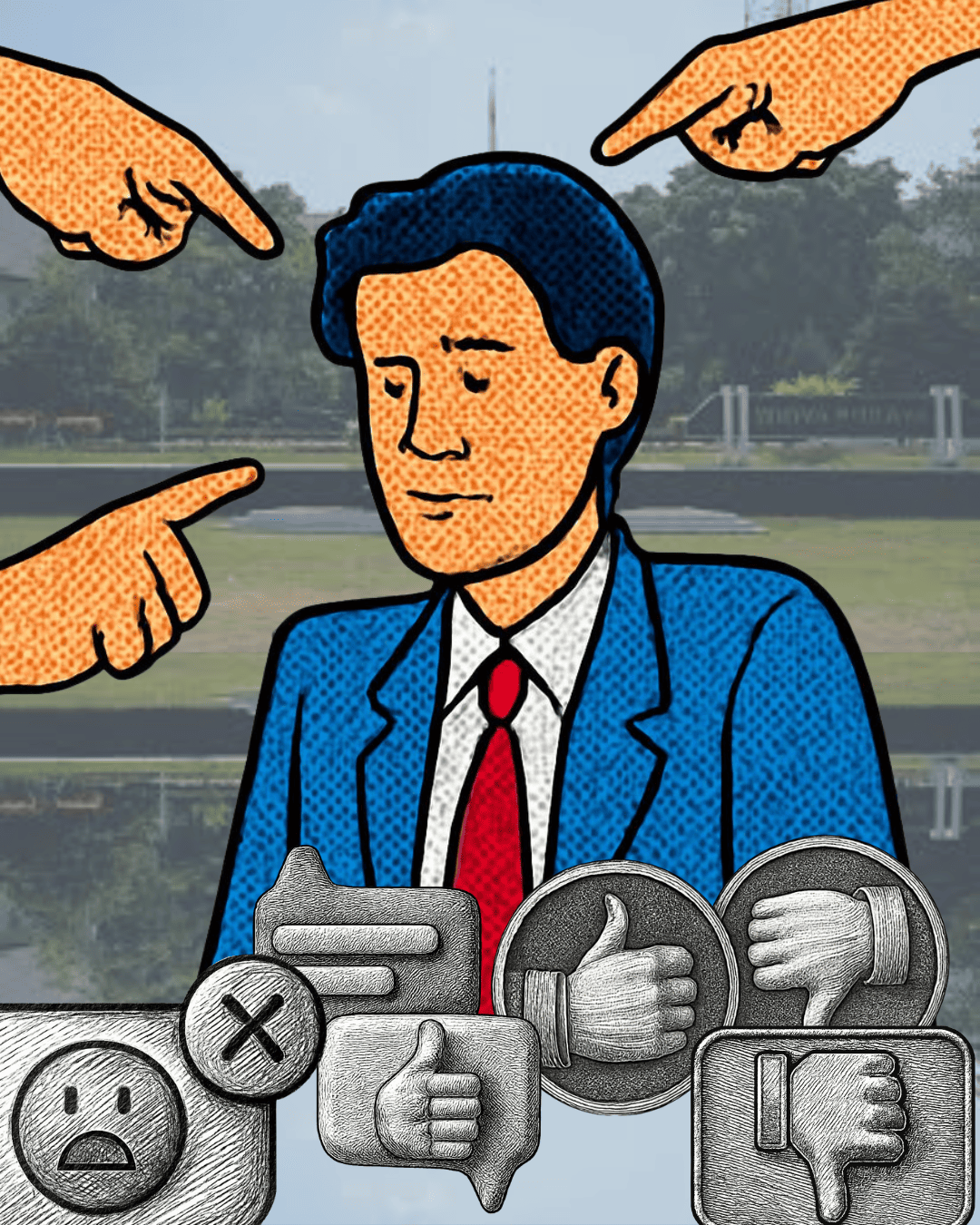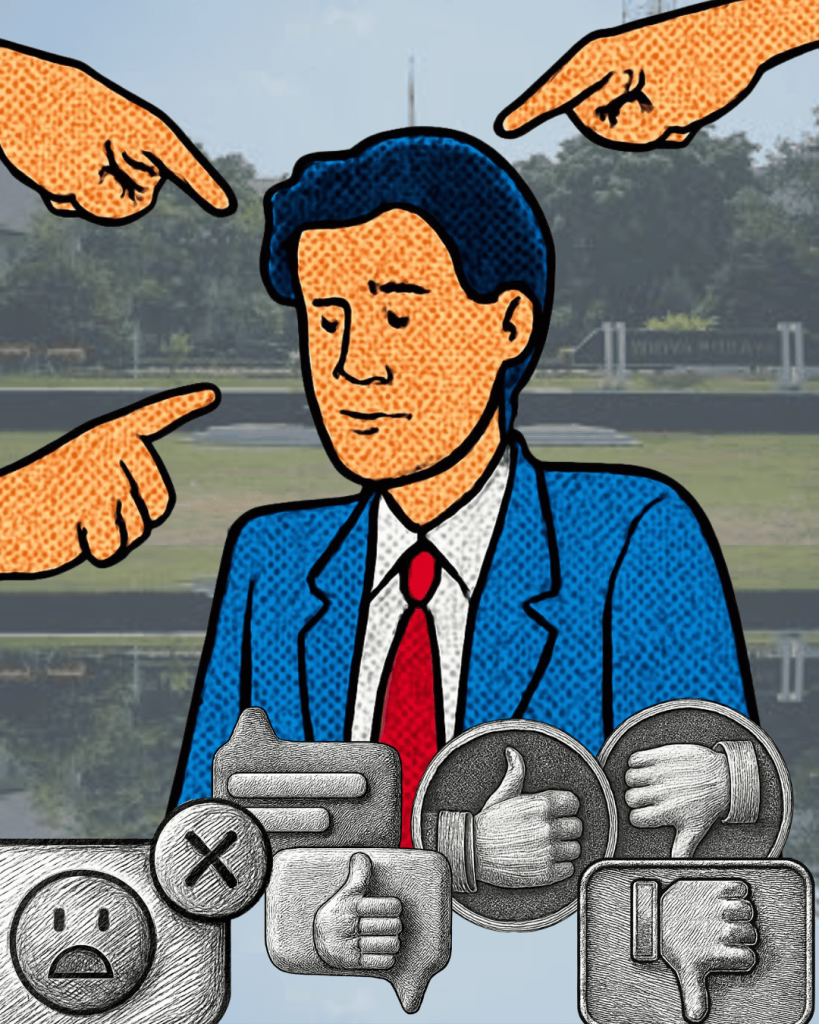
Ada perasaan yang mengganjal tiap kali menilik beberapa kawan yang menanggapi pelbagai pencapaian Undip secara sauvinistik. Memang, ada perasaan “belong” yang tidak dapat kita negasi, dan hal tersebut merupakan perihal organik yang manusiawi. Saya pun setuju, bahwa pencapaian yang ada, perlu untuk kita rayakan bersama. Akan tetapi, mungkin kalian juga sependapat, bahwa segala sesuatu yang berlebihan, tak akan pernah berakhir baik.
Terlalu mengidolakan institusi atau apa pun itu, membawa kita tumbuh menjadi seorang apologist—membenarkan seperangkat tindak-tanduk sang idola karena perasaan obsesif. Mendukung almamater secara ugal-ugalan tak akan membawa kita ke mana-mana, selain menjadi buta dan tuli terhadap masalah yang terjadi di rumah sendiri.
Seyogianya manusia sebagai pengkarya, sudah semestinya akan kita temukan secercah cela atau kekurangan di dalamnya. Memperbaiki, merupakan usaha yang dapat dijamah untuk kebaikan bersama. Tentu, sebelum kita sampai ke tahap memperbaiki, diperlukan orang-orang yang dengan senang hati mampu menunjukkan kerusakan di sana-sini.
Banyak masalah yang dapat kita selidiki dari kampus kita sendiri. Misalnya saja kurangnya akses trotoar di sekitar Tembalang, terbatasnya armada bus kampus, proses administrasi riset yang amburadul, nihilnya transparansi pengelolaan keuangan, hilangnya beberapa mata air setelah Undip didirikan, kurangnya partisipasi-aktif civitas Undip terhadap masyarakat sekitar, koleksi buku di perpustakaan yang tergolong masih kurang, dan daftar permasalahan lain yang saya yakini masih panjang.
Setiap kali saya mencoba mengajukan permasalahan di atas dalam forum diskusi, salah satu jawaban kontra yang paling sering terdengar adalah, “Jangan membuat masalah horizontal, musuh kita jelas dan satu, pemerintahan!” Benar, kini pemerintah kita adalah mimpi buruk terbesar. Benar, kita perlu bersuara untuk itu atas nama keadilan.
Namun, menelaah masalah yang ada di rumah juga perlu, sebab sebagai mahasiswa, institusi pendidikan adalah fondasi utama pergerakan. Bagaimana mungkin kita bisa merobohkan besi, beton, dan bangunan pemerintahan bila di dalam rumah pendidikan, di mana kita dibentuk, yang kita temui adalah kebobrokan?
Kita semua sudah paham, bahwa institusi pemerintahan yang buruk, hanya akan menghasilkan produk hukum, dan kebijakan politik yang sama buruknya. Saya kira, argumen tersebut juga harusnya berlaku pada ragam bentuk institusi, dan tak terkecuali, institusi pendidikan. Bila tempat kita belajar bobrok, lantas mungkinkah kebobrokan itu menghasilkan sesuatu yang gemilang? Saya rasa tidak.
Seumpama mesin espresso yang telah rusak, maka kopi yang dihasilkan tak akan pernah sempurna. Kita akan temukan espresso yang tak miliki krema, over-ekstraksi, rasa yang tak optimal, atau kecacatan lain pada produknya. Oleh karena itu, agar produksi espresso lebih maksimal, perlu adanya pembersihan rutin, pengecekan pasokan air, dan pemeriksaan berkala pada mesin, demi rasa aman, dan kepercayaan para pelanggan.
Proses perbaikan harus dilakukan dengan komitmen penuh, tak boleh setengah-setengah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan gestur populis sementara. Seperti membuat pernyataan sikap, serta poin tuntutan kepada publik, tetapi tidak mengawalnya, dan tidak punya aksi lanjutan untuk menunjukkan komitmen terhadap pernyataan yang telah dilempar.
Kumpulan profesor kala pemilu, tuntutan pada aksi #ResetIndonesia di Widya Puraya September lalu—ketimbang pernyataan sikap, rasanya hanya seperti seremonial belaka agar tak disangka tuli dan buta. Saya tidak melihat kehadiran dosen yang berkomitmen tinggi untuk benar-benar melawan, atau mengebiri pemerintahan. Saya pun tidak menyalahkan, para tenaga pendidik perguruan tinggi punya beban selangit untuk diselesaikan. Hanya saja, sedikit menyayangkan.
Tak ubahnya dengan BEM Undip, yang keluar dari BEM SI karena dirasa terlalu dekat dengan orang-orang istana, tapi di kemudian hari mendatangkan Menteri Pertanian pada anjangsana Orientasi Dipo Muda (ODM). Sikap-sikap “keras” yang diambil jadi terasa hambar, hanya jadi kata tanpa pemaknaan.
Perlu pula saya tegaskan, bahwa yang saya lakukan bukan membuat konflik horizontal, tetapi usaha menyadarkan untuk mempertanyakan diri, sebelum asyik bergulat dengan sesuatu yang lebih besar. Lawan kita adalah pohon rezim yang telah busuk sampai ke akar-akarnya dan hanya tanah sehat yang mampu mendekomposisikan pohon busuk itu secepat-cepatnya.
Sebelum bermimpi besar meradikalisasi sistem pemerintahan dengan warna pergerakan non-kooperatif. Hendaknya kita perlu jua meradikalisasi sistem pendidikan di tingkat universitas. Berbeda dengan SD, SMP, dan SMA yang sepenuhnya telah dinasionalisasi, dan telah menjadi alat produksi pemerintah—universitas di lain sisi, punya kendali lebih besar terhadap dirinya sendiri. Kendati demikian, mengapa tidak kita manfaatkan?
Aktivisme yang dapat kita lakukan tak semerta langsung membuat demonstrasi berkepanjangan di depan gedung rektorat. Mulai saja dengan membicarakannya bersama kawan tongkrongan di tempat kalian beserikat. Menyebarkan isu ini kepada setiap kelompok secara getok-tular adalah salah satu cara ampuh untuk mengonsolidasikan ide dan pemikiran.
Satu topik pembahasan yang kalian bawa sebagai bahan diskusi, suatu saat akan merekah menjadi gerombol keresahan warga-wargi. Akan ada masanya keresahan itu mengepul lalu menyesakkan kepala dan hati. Bila itu terjadi, maka runtutan aksi-aksi niscaya akan bermekaran secara organik.
Baik, saya rasa sekian saja ocehan kali ini. Jangan lupa untuk kritisi kembali tulisan ini dengan kawan-kawan sekitar. Sebagai penutup, saya akan menyajikan kutipan Slavoj Žižek, pada salah satu kutbahnya yang terpampang di laman YouTube pada kanal Big Think—yang juga menjadi pemantik dari tulisan ini.
“The danger today is precisely a kind of a bland, pragmatic activism. You know, like when people tell you: ‘Oh my God, children in Africa are starving and you have time for your stupid philosophical debates? Let’s do something!’ I always discern in this a more ominous injunction: Do it and don’t think too much. Today, we need thinking.”
Penulis: Hanan Khairul Tamama (Kontributor)