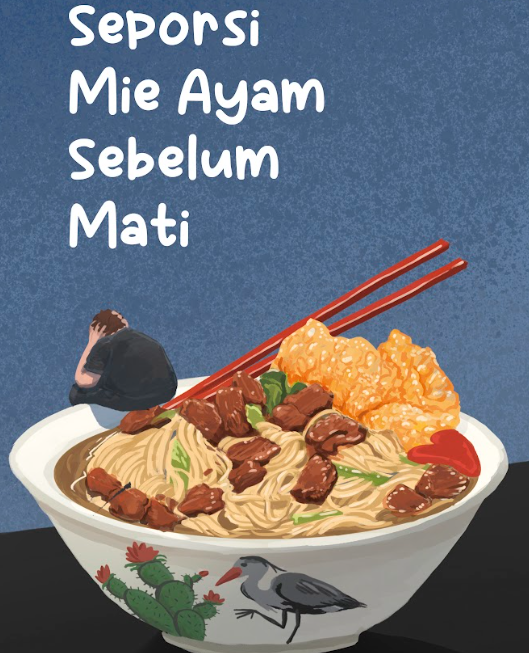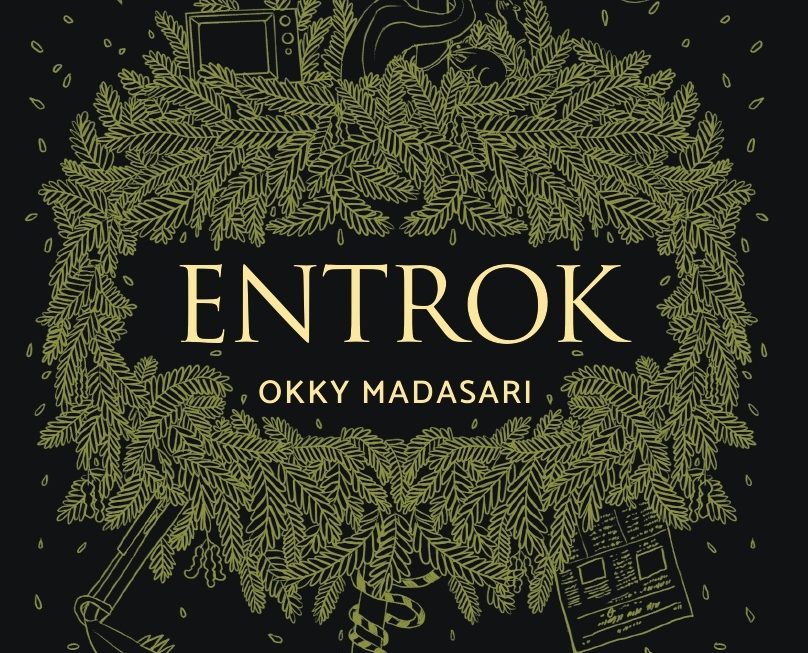Identitas Buku:
Penulis: Ahmad Tohari
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Jumlah Halaman: 71 halaman
Tahun Terbit: 1989
Cetakan ke-: 16, Februari 2025
ISBN: 9789792297362
Senyum Karyamin, buku berisi 13 judul cerita pendek yang menganut paham kesederhanaan, kemiskinan, dan kepayahan. Berlatarkan pedesaan atau gang-gang kecil beraroma kesepian dan keblingsatan, kumpulan cerita pendek karya Ahmad Tohari ini mampu menarik pembaca ke dalam pengalaman-pengalaman kecil yang penuh makna.
Akar dari berjalannya pengalaman membaca buku ini adalah Fear of Missing Out (FOMO). Sejujurnya, saya jarang sekali merasa FOMO terhadap hal-hal yang naik daun. Namun, persoalan buku dan dunia baca berbeda, terutama karena saya tengah berjuang menambah pengetahuan melalui bacaan sastra Indonesia.
Sastra Indonesia itu memikat, dan seperti nikotin, mereka mendorong para pembaca untuk terus penasaran terhadap ceritanya. Begitulah saya di suatu hari yang cukup panjang; mempertimbangkan buku apalagi yang sebaiknya saya beli dan baca untuk mengisi hari. Saya yang sejak kecil kecanduan buku terjemahan, kini terkungkung dalam rasa penasaran terhadap karya Anak Bangsa.
Di kemudian hari, saya bertemu karya-karya penulis pemula dari penerbit indie. Di hari lain, saya bertemu penulis buku non-fiksi—feminisme dan kesehatan mental—karya seorang feminis Indonesia dan seorang psikolog. Lalu, saya dipertemukan kepada karya-karya Intan Paramadhita yang spontan saya nobatkan menjadi penulis favorit saya. Hari berikutnya, karena saya belum mampu membeli Ronggeng Dukuh Paruk, maka saya memulainya dengan buku tipis nan mungil: Senyum Karyamin.
Merakyat dalam Balutan Alur yang Sederhana
Terus terang saja, cerita pendek favorit saya dalam Senyum Karyamin berjudul Rumah yang Terang. Judul tersebut menyajikan kisah tentang kampung tanpa listrik yang akhirnya menjadi terang, namun seorang lelaki enggan memasang listrik di rumahnya. Menurut saya, itu cerita paling sederhana dan straight to the point.
Lalu, ada juga tentang Blokeng yang mengandung jabang bayi tanpa ayah lalu membuat geger para warga. Kisah dalam judul Blokeng itu cukup menghibur karena di akhir, si Blokeng dan anaknya tertawa.
Kemudian, ada cerita pendek berjudul Pengemis dan Shalawat Badar. Akhir dari cerita itu cukup tragis, namun menakjubkan. Ahmad Tohari seperti mengingatkan pembaca untuk terus ingat kepada Yang Kuasa agar selamat perjalanan di akhirat, dan, ada beberapa judul lain yang tak kalah menyenangkan untuk dibaca.
Ciri khas yang diagungkan: KESEDERHANAAN DAN DUNIA “ORANG KECIL” rupanya dieksekusi begitu ciamik dan apik. Saya terkesima membaca karya tangan penulis senior tersebut. Penggunaan bahasa dan bagaimana ia ‘mendongeng’ seperti mengantar kita untuk tidur lelap sebab duniamu lebih baik dari mereka—para tokoh utama.
Benar kata Sapardi Djoko Darmono dalam Kata Penutup, Ahmad Tohari hanya mendongeng. Lalu, pembaca dibiarkan menelan dan menelaah kisah-kisah itu dengan mandiri. Memahami maknanya dan merenungkannya seorang diri.
Kata-kata baru seperti: pongah, keblingsatan, dan masygul menambah pengetahuan kebahasaan saya. Kata-kata itu terdengar seperti sangat lawas, sehingga jarang sekali saya temukan dalam buku-buku masa modern. Saya senang membaca kata-kata baru karena memberikan kesegaran dalam membaca.
Setiap cerita pendek menyajikan konflik yang sederhana dan tidak ‘muluk-muluk’. Kisahnya sangat merakyat, bisa saya temukan di dunia nyata. Hanya saja, jarang diperdengarkan kepada khalayak. Konflik-konflik sederhana yang sebenarnya perlu diperhatikan dan diperbincangkan itu seperti tersembunyi, lalu meleleh dalam karya Ahmad Tohari.
Selain itu, saya takjub dengan cara Ahmad Tohari mengeksplor nama-nama asing yang tak pernah saya temukan. Nama seperti Kenthus, Dawet, Blokeng, Musgepuk, Kimin, dan lainnya terdengar begitu orisinal. Mendorong saya untuk percaya bahwa “Inilah tokoh ciptaan Ahmad Tohari,” dan tak seorang pun mampu memakai nama seunik ini.
Gaya penulisannya cukup unik, namun tak menakjubkan. Terdampar seperti tulisan-tulisan sastra lawas yang bisa diimitasi penulis lainnya. Namun, menceritakan tokoh orang kecil tampaknya keahlian Ahmad Tohari. Sebab, kesederhanaan tak melulu jadi poin pentingnya. Namun, kisah bermakna dalam konflik sederhana itulah yang menjadi daya pikat.
Pembaca pemula seperti saya sepertinya harus banyak membaca buku karya Ahmad Tohari. Terlebih, saya inilah orang kecil yang disinggungnya dalam cerita pendek itu. Meskipun kehidupan saya tidak memprihatinkan, saya merasa begitu dekat dengan konflik yang dituliskan.
Sayangnya, beberapa cerita justru tidak to the point dan membuat saya bingung makudnya. Namun, kebingungan itu hilang setelah saya menemui Rumah yang Terang. Saya jadi paham, Ahmad Tohari suka menyajikan makna-makna begitu gamblang, hanya para pembaca kesulitan menyatukan potongan puzzle-nya. Pembaca hanya diajak meneruskan kisah, dan harus kembali lagi untuk menemukan artinya.
Alasan Pendek untuk Buku yang Pendek Pula
Mungkin, beberapa orang berpikir, keputusan saya membeli buku Senyum Karyamin ini didasari oleh rasa keingintahuan terhadap Ahmad Tohari. Benar, begitu. Namun, yang terutama adalah saat itu saya mendapati buku ini di sebuah marketplace dengan harga sangat terjangkau. Entah, mungkin tak sampai lima puluh ribu rupiah.
Saya membaca buku ini dalam jangka waktu yang sangat panjang. Padahal, bukunya sangat singkat. Sekali duduk pun ludes. Sayangnya, buku ini di awal cukup membosankan dan membingungkan. Nah, alasan kedua ini cukup krusial mengingat daya tarik dari buku ini adalah dengan gamblangnya Ahmad Tohari mendongeng tentang kesederhanaan.
Lalu, alasan saya menamatkan buku ini adalah karena perasaan saya terdorong untuk tidak menghakimi mahakarya ini. Saya diminta dengan teliti menelisik ke dalam kisah-kisah si tokoh utama. Mendalami kehidupan Blokeng, Minem, Kenthus, hingga Samin. Kehidupan mereka di kampung yang pongah, atau terjun ke dalam mimpi nunggang macan.
Dan, ketika mata saya menemukan “Kata Penutup dari Sapardi Djoko Darmono,” perasaan cemas dan kecewa menggerogoti relung hati. Saat membaca penutup itu, saya sadar, rupanya saya tak memahami apa-apa. Saya belum memahami kesederhanaan dalam balutan konflik ringan dari tokoh-tokoh sebagai rakyat kecil. Saya terlalu egois karena menginginkan alur yang lebih dramatis, padahal Ahmad Tohari mencintai kebebasan dalam kesederhanaan itu.
Di situlah, saya menutup buku. Menarik napas, dan memutuskan untuk membeli buku karya Ahmad Tohari lagi.
Penulis: Marricy
Editor: Diaz