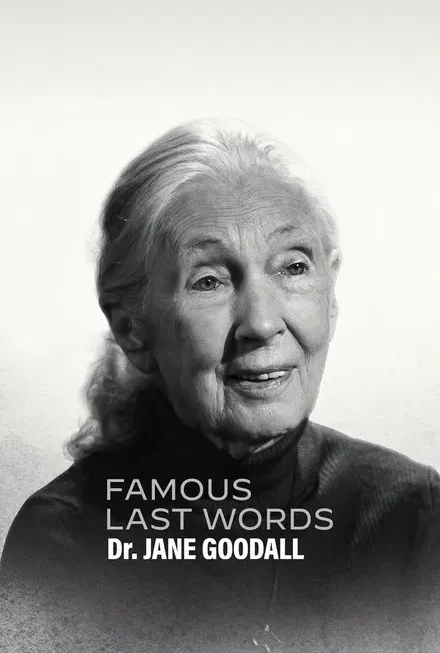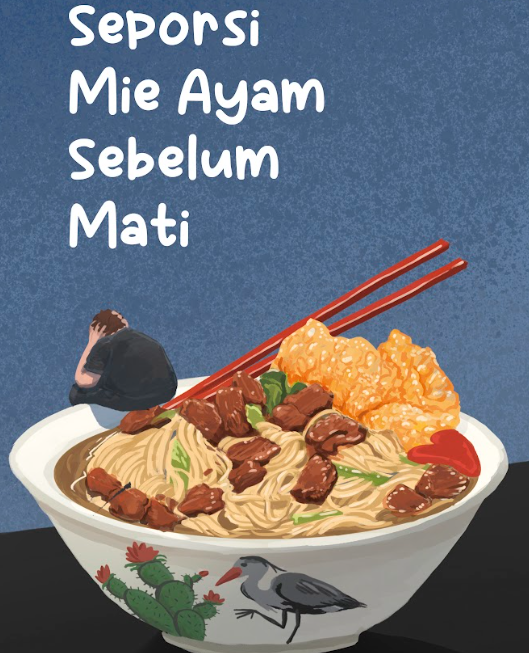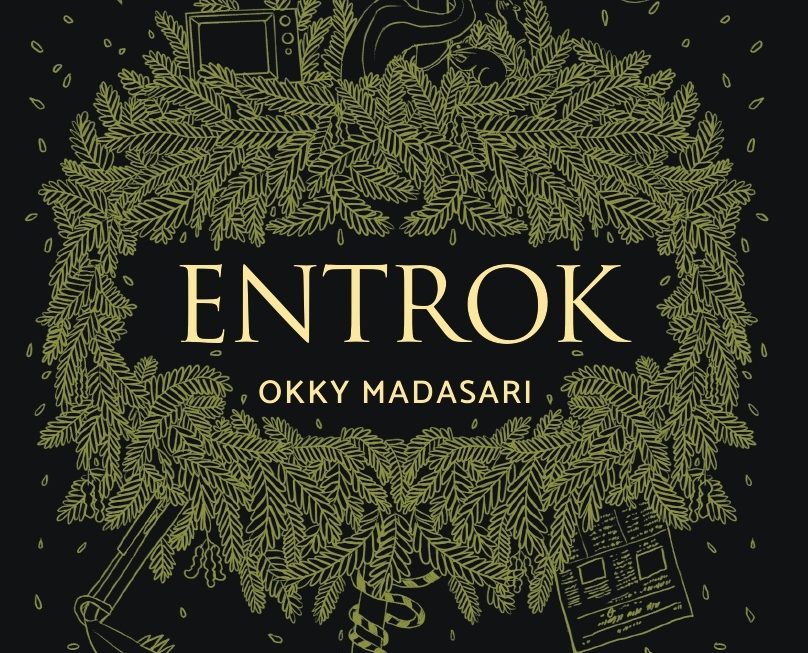Judul: Hiroshima: Ketika Bom Dijatuhkan
Penulis: John Richard Hersey
Penerbit: Komunitas Bambu
Cetakan: 1, 2008
Halaman: 172 hlm
Dimensi: 11.5 x 17.5 cm
ISBN: 979-3731-29-x
Saya teringat ketika mata kuliah Sejarah Asia Timur dan Selatan dalam salah satu pembahasan materi mengenai masa Jepang Zaman Showa yang menyinggung mengenai keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. Ketika perang sudah mencapai babak finalnya, sekutu mengeluarkan Deklarasi Postdam bertanggal 26 Juli 1945 yang menyatakan agar Jepang segera menyerah atau dibinasakan. Maka selama beberapa bulan menjelang perang berakhir, kota-kota besar di Jepang dibom melalui udara oleh sekutu seperti yang digambarkan dalam film Grave of The Fireflies besutan Isao Takahata. Jepang tidak pernah menyangka jika ancaman dari pihak sekutu yang akan membinasakan negara mereka merupakan ancaman serius, bukan sekadar omong kosong belaka. Setelah dua minggu kemudian, pesawat B-29 yang membawa bom atom uranium “Little Boy” jatuh di timur laut Hiroshima, 6 Agustus 1945. Peristiwa itu menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah.
Dari materi ini, timbulah sebuah diskusi menarik dengan sebuah pertanyaan, apakah Jepang layak dijatuhkan bom atom sebagai konsekuensi mereka dalam keterlibatan Perang Dunia II? Ada dua pandangan mengenai tragedi ini, pertama bagi mereka negara yang diduduki Jepang selama Perang Dunia II menyatakan bahwa dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan balasan terkait kejahatan perang yang telah mereka lakukan terhadap negara-negara di wilayah Asia-Pasifik, bahkan menjadi momentum bagi negara-negara tersebut untuk merdeka. Kedua, para pandangan humanis Barat menyatakan bahwa tragedi tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM berat karena melibatkan banyak korban jiwa dari warga sipil. Kedua pandangan tersebut masih diperdebatkan hingga saat ini, bahkan Amerika Serikat hingga saat ini tidak memberikan kata maaf telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Perdebatan pro dan kontra mengenai dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membawa saya mengingat kembali ketika diperkenalkan salah satu karya jurnalisme sastrawi terpenting di abad ke-20, yaitu Hiroshima yang terbit pada 23 Agustus 1946 lalu di The New Yorker. Perkenalan saya dengan buku Hiroshima terjadi ketika Magang Madya LPM Hayamwuruk 2021 oleh salah satu pembicara, Fahri Salam, eks jurnalis Tirto.id yang kini memimpin dapur redaksi Project Multatuli. Sebagai anak Sejarah yang mengetahui bahwa karya dari John Hersey masuk kriteria feature terbaik menurut Fahri Salam, saya mencoba mencarinya. Sebuah keberuntungan bagi saya bahwa Hiroshima bisa diakses secara gratis melalui laman media The New Yorker, hingga akhirnya saya mengetahui bahwa karya John Hersey ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bentuk buku fisik oleh Komunitas Bambu.
Hiroshima merupakan laporan jurnalistik berformat naratif, sehingga John Hersey sukses membawa kita merasakan apa yang terjadi di setiap karakter dalam menanggung rasa sakit. Buku ini bercerita tentang enam penyintas bom atom Hiroshima yang memiliki karakter dan profesi yang berbeda namun berbagi kemalangan yang sama. John Hersey membagi cerita menjadi enam babak, satu babak untuk satu karakter, yang kemudian menjadi satu cerita ketika bom atom dijatuhkan. Dengan membagi cerita ke setiap karakter, kita bisa melihat bagaimana aktivitas “normal” setiap karakter dalam menghadapi kondisi perang sebelum “tuan b-29” menjatuhkan “Little Boy” di Hiroshima. Misalnya, Nyonya Hatsuyo Nakamura yang baru saja mengantarkan kedua anaknya tidur sambil memandangi rumah tetangganya yang harus dirobohkan karena masuk di jalur api. Dokter Terufumi Sasaki yang sedang berjalan di koridor rumah sakit sambil membawa spesimen darah untuk tes wasserman. Atau Nona Toshiko Sasaki yang sedang berbicara dengan gadis di sebelahnya. Mereka tidak akan memperkirakan 2-5 menit ke depan kehidupan mereka akan berubah.
“Seratus ribu orang terbunuh oleh bom atom dan keenam orang ini adalah sebagian dari mereka yang selamat. Mereka masih saja bertanya-tanya, mengapa mereka tetap hidup ketika begitu banyak orang lain mati . . .”
Buku ini memiliki 172 halaman dengan ukuran A5 atau ukuran kantong. Saya sempat berekspektasi bahwa buku ini akan memiliki ukuran A4 seperti buku pada umumnya. Saya sempat meragukan bahwa dengan ukuran buku sekecil ini apakah mampu memberikan kenyamanan membaca kepada para pembacanya atau malah membuat pembacanya merasa kurang nyaman. Keraguan saya terbayar tuntas, walaupun berukuran kantong buku ini mampu memberikan pengalaman membaca yang berbeda. Untuk terjemahan menurut saya agak sedikit kaku dibanding versi digital dari The New Yorker. Kedua versi memiliki karakteristik masing-masing dan kelebihan yang ditawarkan, namun keduanya akan membawa Anda untuk ikut masuk merasakan pedih yang penyintas rasakan. Sebagai anak Sastra dan Sejarah, buku ini cocok untuk masuk ke dalam wishlist membaca kamu.
Happy reading ~
Penulis: Hawari Jaelani Fadilah
Editor: Rilanda