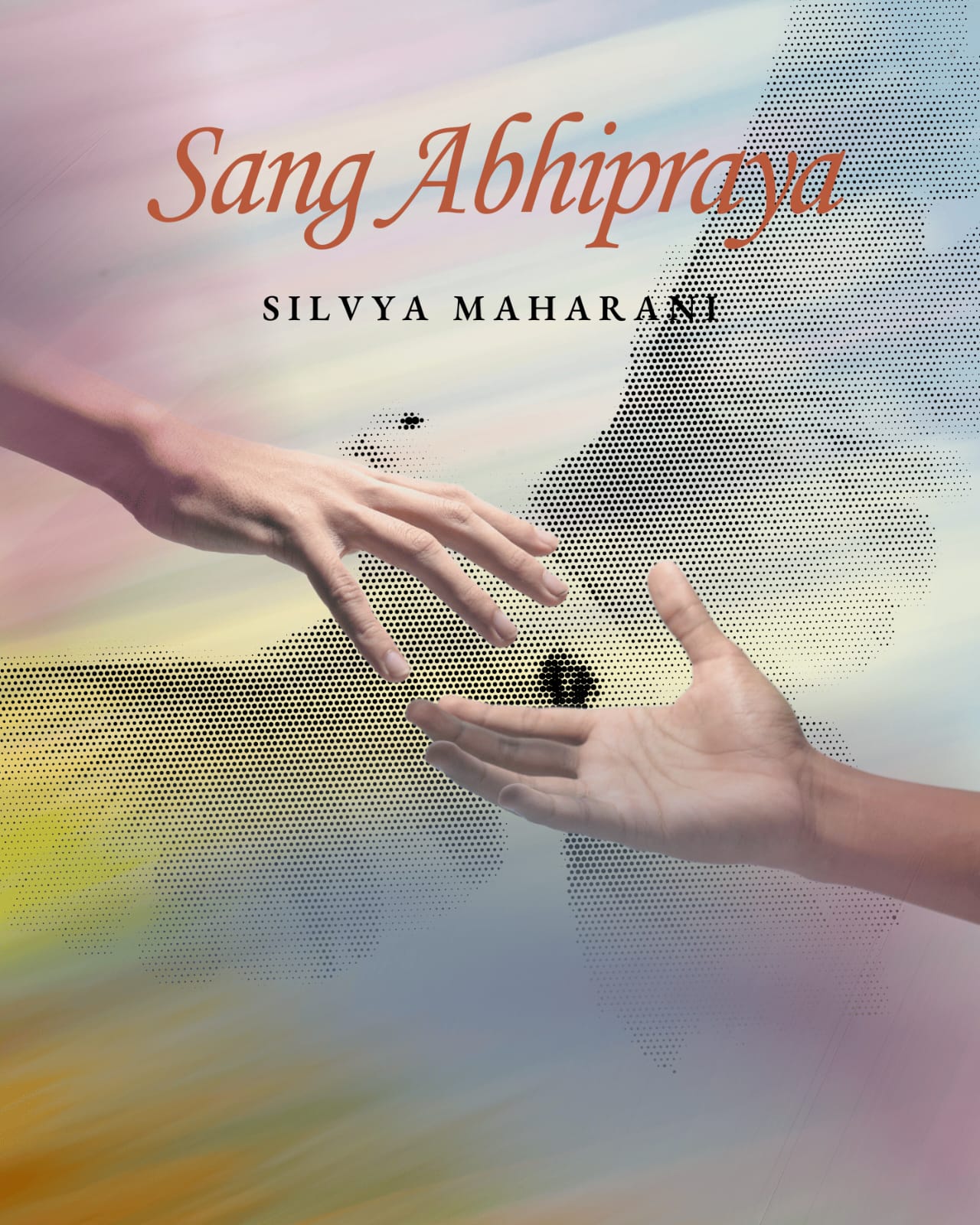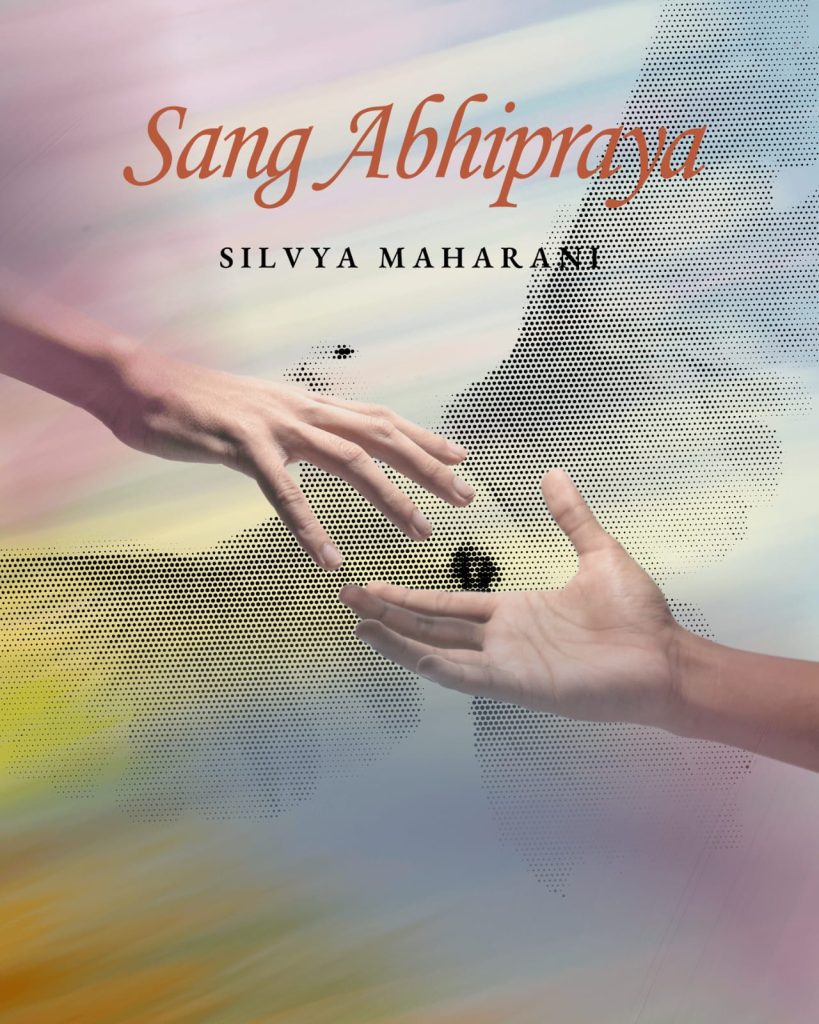
“Kecelakaan maut pada tanggal 16 April di Surakarta, terjadi antara truk dan mobil menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang luka parah serta 7 orang lainnya luka ringan.”~ tvUni.
Setahun setelah kejadian itu, Prawira yang akrab dipanggil Wira mengurung diri di rumah. Ia mengalami luka parah yang mengharuskannya menjalani amputasi pada kaki kirinya. Namun, luka di jiwanya jauh lebih dalam. Ia tak hanya kehilangan anggota tubuh, tetapi juga kehilangan arah, semangat, dan kepercayaan terhadap hidup.
Hari-hari Wira dihabiskan dalam diam. Jendela kamarnya tertutup rapat, udara pengap dan gelap menjadi teman setianya. Ia menolak melihat cahaya matahari, seolah dunia diluar sana hanya akan menyakitinya lebih dalam. Ia enggan berbicara dengan siapa pun, kecuali Bapak dan Ibunya, Pak Rahmat dan Bu Siti. Meski Bapak dan Ibu Wira telah berusaha membujuknya agar bersedia menerima tamu yang ingin menjenguk, Wira selalu menolak dan setiap upaya komunikasi dari teman-temannya, hanya berujung pada penolakan dingin atau diam yang membeku. Bahkan, ketika mereka memaksanya untuk sekadar keluar kamar atau duduk bersama di ruang keluarga, Wira kerap meledak dalam amarah. Ia tak segan membanting barang-barang di sekitarnya, meluapkan rasa sakit yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata.
Wira tenggelam dalam duka yang tak terlihat, dan dunia seakan ikut membisu bersamanya.
Bapak dan Ibu Wira selalu hadir dengan kesabaran dan perhatian, meski putra semata wayangnya terus menarik diri setiap kali diajak berbicara. Mereka tak pernah menyerah, terus mengetuk pintu hati Wira yang seolah terkunci rapat. Hingga pada suatu ketika, suara benda jatuh terdengar dari kamar Wira. Pak Rahmat dan Bu Siti langsung berlari ke sana. Pintu kamar tidak dikunci. Mereka mendapati Wira duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, dan di tangannya tergenggam sebuah cutter. Di pergelangan tangannya, terdapat goresan merah belum terlalu dalam, tapi cukup membuat darah menetes ke lantai.
“ASTAGHFIRULLAH NAKK!!!” teriak Bu Siti sambil gemetar. Ia segera mengambil cutter itu dari tangan Wira.
Pak Rahmat langsung merengkuh tubuh Wira ke dalam pelukannya. “Istighfar, Nak… Astaghfirullah…” bisiknya, berusaha menenangkan putranya yang masih terdiam, dengan mata kosong memandangi ruang hampa.
Air mata mulai mengalir dari sudut mata Wira. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Bukan karena rasa sakit dari luka di pergelangan tangannya, melainkan luka di hati yang begitu lama tak ia ungkapkan.
“Jangan pernah sakiti dirimu,disini ada bapak dan ibu yang selalu ada untukmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu apapun keadaannya, kamu tidak pernah sendiri. Ceritakan semuanya pada bapak dan ibu apapun yang sedang kamu rasakan nak, jangan kamu pendam sendiri yang akhirnya menumpuk lalu meledak dan mengacaukan pikiranmu, lakukan apapun yang membuatmu lebih tenang tetapi tidak dengan menyakiti dirimu sendiri seperti ini.” Ucap bapak yang berusaha menenangkan Wira sambil mengusap rambut Wira.
Bu Siti hanya bisa menangis pelan, menggenggam tangan Wira erat-erat seolah ingin menyalurkan kekuatan lewat sentuhan itu.
Wira mulai berbicara dan membalas pelukan bapak dengan erat “Pak,bu…sampai kapan Wira harus berada di kondisi seperti ini? Wira capek pak..bu…”
Bapak melepaskan pelukannya lalu menangkup pipi Wira dan menatapnya dengan tegas “Nak, Tuhan itu adil. Apa pun yang kita alami, entah itu kegagalan, kehilangan, atau kebahagiaan, semuanya datang membawa makna. Kadang kita jatuh begitu dalam supaya kita tahu rasanya dikuatkan oleh-Nya. Saat kamu merasa benar-benar rapuh… Tuhan ada. Memelukmu. Tapi sering kali kita terlalu larut dalam rasa sakit hingga lupa menoleh pada-Nya.”
Wira menunduk, air matanya mengalir deras “Tapi pak, kenapa harus Wira, kenapa dari banyaknya manusia di dunia ini Wira juga yang harus menerima dan menanggung kondisi yang menyedihkan seperti ini?? Kenapa Tuhan memilih Wira??”
Pak Rahmat menggeleng pelan, suaranya tenang tapi penuh keyakinan “Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan nak untuk semua yang terjadi, untuk semua yang kita alami karena semua itu sudah takdir sekarang kita hanya bisa berserah meminta belas kasihan Tuhan dan belajar ikhlas menerima semua nya, tolong usaha untuk ikhlas ya nak? Bapak dan ibu akan selalu ada disampingmu”
Wira terdiam, matanya menatap wajah kedua orang tuanya, ia mulai memahami bahwa cinta dan dukungan yang tulus tak pernah pergi.
Sang Abhipraya (harapan) tumbuh diam-diam dalam jiwa Prawira.
Di sepanjang perjalanan ini, menjadi ruang belajar bagi kita. Untuk memupuk kesabaran dan keikhlasan agar terus tumbuh dalam hati. Dua hal sulit yang seiring waktu bisa benar-benar kita lakukan melalui orang-orang yang datang. Melalui ujian yang silih berganti. Melalui perpisahan-perpisahan yang kacaukan hati. Melalui pencapaian yang harus diperjuangkan dengan berlelah-lelah tiada henti. Juga melalui apa saja yang didatangkan-Nya setiap hari.
Ruang belajar itu ada di sepanjang perjalanan kita ini. Yang belum tentu setiap orang menggunakannya untuk belajar. Bisa jadi dilewatkan begitu saja. Hingga seiring berjalan-nya waktu, kesabarannya tidak juga bertambah, keikhlasannya tidak juga tumbuh dengan baik, pun dengan kebijaksanaannya menghadapi segala sesuatu semua tidak bertambah.
Sebab di perjalanannya, la enggan untuk mengambil pelajaran Enggan untuk memungut kebaikan yang terselip dari apa pun yang didatangkan-Nya. Entah pada kesedihan, duka mendalam, kebahagiaan, kedatangan seseorang, perpisahan dengan orang- orang tersayang, kegagalan, keberhasilan yang kadang melenakan, dan lain sebagainya.
Sedangkan Tuhan menyelipkan begitu banyak kebaikan yang harus kita ambil di dalamnya Dengan pikiran yang jernih, hati yang luas, juga keyakinan pada-Nya yang tak pernah berbatas.
Maka semoga, kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersedia belajar. Senantiasa pandai memungut kebaikan yang diselipkan Tuhan di balik setiap persoalan yang datang-apa pun itu. Jadi, selamat belajar untuk ikhlas.